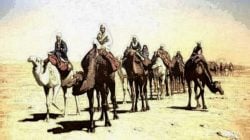Oleh: Rusdianto Sudirman
Dosen Hukum Tata Negara IAIN Parepare
Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai penghormatan kepada Ki Hadjar Dewantara, pelopor pendidikan Indonesia yang menanamkan prinsip mendasar pendidikan harus membebaskan manusia. Namun, dalam dunia pendidikan tinggi kita hari ini, kebebasan itu kian menjauh. Perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi rumah bagi pencarian ilmu, pembentukan karakter, dan pengabdian pada masyarakat, justru tersandera oleh budaya administratif dan obsesi semu terhadap peringkat.
Hari ini, wajah pendidikan tinggi Indonesia berubah menjadi industri sertifikasi dan kompetisi administratif. Kampus sibuk mengejar akreditasi, dosennya dipaksa menulis di jurnal bereputasi semata-mata demi angka kredit dan gelar akademik, sementara mahasiswa dibentuk menjadi lulusan cepat saji yang akrab dengan borang, tapi tidak laku di masyarakat.
Tak bisa dipungkiri, dalam lingkungan akademik hari ini, profesor bukan lagi gelar yang diraih karena kebijaksanaan dan kontribusi terhadap ilmu, melainkan karena ketangkasan mengisi borang dan mengejar Scopus. Ini bukan berarti publikasi internasional tidak penting. Namun ketika menulis menjadi tujuan, bukan alat untuk membangun gagasan, maka riset kehilangan rohnya. Banyak tulisan yang lahir bukan dari keresahan akademik, melainkan dari kewajiban administratif. Tak heran jika banyak publikasi kita tidak berdampak, bahkan tidak pernah dikutip.
Lebih ironis, semakin tinggi jabatan akademik dosen, semakin jauh mereka dari ruang-ruang kelas. Mahasiswa kehilangan figur inspiratif di ruang kuliah, digantikan asisten dan presentasi PowerPoint yang diseragamkan. Interaksi edukatif yang bermakna sebagaimana ditekankan Ki Hadjar Dewantara mulai menghilang.
Perguruan tinggi tak ubahnya perusahaan jasa pendidikan yang berorientasi pada nilai akreditasi dan perangkingan. Lembaga akreditasi seperti BAN-PT dan LAM tumbuh menjadi kekuatan yang menentukan arah kampus, bukan lagi visi akademik. Kampus berlomba mempercantik dokumen, menumpuk administrasi, dan mengejar indikator kuantitatif seperti jumlah jurnal, lama studi, rasio dosen mahasiswa, dan jumlah dana hibah.
Sayangnya, semua itu kerap dilakukan sebagai formalitas. Banyak kampus yang mengatur strategi “pemalsuan data” demi akreditasi unggul, sementara realitas pendidikan tetap memprihatinkan. Mahasiswa tidak benar-benar mendapatkan pengalaman belajar yang otentik, dan dunia kerja kerap kecewa dengan kualitas lulusan.
Sistem pendidikan tinggi kini mencetak lulusan dengan cepat, murah, dan seragam. Mahasiswa dikejar target kelulusan empat tahun, tugas akhir disederhanakan, bahkan seminar hasil dan sidang skripsi menjadi formalitas. Banyak yang lulus tanpa pernah benar-benar memahami apa yang mereka pelajari, apalagi menghayatinya.
Kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) yang diharapkan menjadi terobosan, pada praktiknya sering kali hanya menjadi aktivitas ekstra yang dipaksakan, tanpa landasan epistemologis yang kuat. Alih-alih membebaskan mahasiswa memilih jalan intelektualnya, MBKM sering menjadikan mahasiswa buruh magang atau peserta proyek pemerintah. Atau bahkan menjadi karpet merah bagi mahasiswa semester 14 yang terancam Drop Out.
Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah usaha menumbuhkan budi pekerti, kecerdasan, dan keterampilan. Hari ini, kita lebih sibuk pada yang ketiga, dan bahkan yang semu, kompetensi administratif dan gelar. Aspek budi pekerti dan nalar kritis terpinggirkan. Pendidikan seharusnya membentuk warga negara yang cakap berpikir dan bertindak untuk bangsanya, bukan sekadar tenaga kerja yang lulus uji kompetensi.
Jika kita ingin menyelamatkan arah pendidikan nasional, terutama pendidikan tinggi, maka kita harus kembali pada akar. Pendidikan harus dimaknai sebagai proses pembebasan dan pemanusiaan, bukan sekadar pengukuran angka dan dokumen.
Oleh karena itu , menurut penulis yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan sistem pendidikan khususnya perguruan tinggi yaitu Pertama, reformasi sistem penilaian akademik harus dilakukan secara menyeluruh. Penilaian dosen dan institusi tidak boleh hanya berbasis kuantitas jurnal dan angka kredit, tetapi juga dampak nyata terhadap pembelajaran, masyarakat, dan kebijakan publik. Dosen malas mengajar dapat sertifikasi, Dosen rajin justru di persulit dapat sertifikasi.
Kedua, ruang akademik harus dikembalikan pada semangat dialogis. Dosen harus didorong untuk aktif mengajar, berdiskusi, dan membina mahasiswa secara personal. Kultur mentoring harus dikembangkan, bukan sekadar administrasi perwalian.
Ketiga, arah kebijakan pendidikan tinggi harus berpihak pada mutu proses, bukan hanya output administratif. Akreditasi seharusnya berbasis pada capaian pembelajaran nyata, bukan sekadar kelengkapan dokumen.
Keempat, peran mahasiswa sebagai subjek pendidikan harus dikembalikan. Mahasiswa harus diberi ruang bereksperimen, bersuara kritis, dan menjadi bagian dari proses transformasi kampus, bukan hanya konsumen jasa pendidikan.
Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremoni. Ia harus menjadi saat perenungan kolektif. Kita para dosen, birokrat pendidikan, mahasiswa, dan masyarakat harus jujur mengakui bahwa pendidikan tinggi kita sedang berada dalam krisis arah. Dan jika tak segera dibenahi, kita bukan hanya mencetak sarjana tanpa kualitas, tetapi membangun bangsa yang kehilangan jiwa.
Maka di tengah perayaan ini, mari kita pulang ke semangat Ki Hadjar Dewantara, mendidik dengan hati, membimbing dengan akal sehat, dan membebaskan dengan kasih sayang. Pendidikan tinggi bukan soal angka, tapi tentang memanusiakan manusia.
Selamat hari pendidikan nasional.